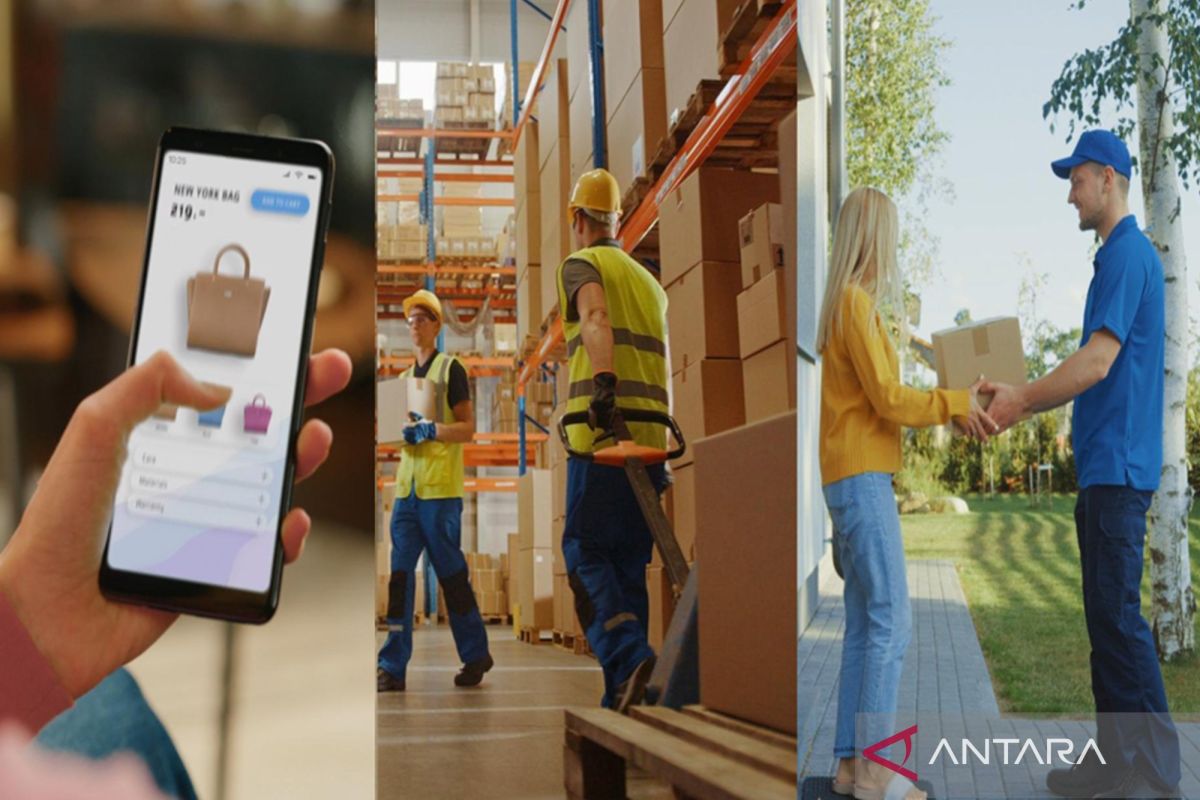Jakarta (ANTARA) - Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas selalu datang seperti pesta kembang api: gemerlap, gaduh, dan membuat siapa pun merasa sedang mendapat keberuntungan besar. Di balik gegap-gempita diskon, ada pertanyaan yang jarang kita berani tengok. Siapa sebenarnya yang menjadi lebih untung: kita yang merasa “berhemat”, atau mesin raksasa yang pandai memoles keinginan menjadi (seolah) kebutuhan?
Setiap memasuki Desember, layar gawai kita berubah seperti pasar malam digital. Lampu-lampu promo berkedip, suara “cekout sekarang!” menggema, dan rasa penasaran mencicit, seperti anak ayam kelaparan.
Harbolnas datang bukan sekadar sebagai perayaan belanja, tetapi sebagai ritual tahunan yang memadukan rasa ingin punya, rasa takut ketinggalan, dan rasa “siapa tahu butuh”.
Di balik gemerlap itu, ada dinamika psikologis yang diam-diam bekerja. Masyarakat kita hidup dalam tekanan ekonomi yang pelik: harga kebutuhan pokok melesat, tabungan tak sempat tumbuh, sementara tuntutan sosial (dari bekerja, dari keluarga, dari media sosial) tak pernah berhenti menggedor. Dalam kondisi seperti ini, diskon besar tampak seperti jendela oksigen. Sejenak kita merasa diizinkan untuk “memperbaiki hidup” dengan harga separuh.
Pada bagian lain, pemerintah mematok target transaksi Harbolnas hingga Rp35 triliun untuk menopang konsumsi domestik dan penjualan produk lokal, namun belum ada aturan kuat soal transparansi harga, sehingga konsumen sering kesulitan menilai apakah diskon itu sungguhan atau sekadar trik dari angka dasar yang dinaik-turunkan. Sementara suara literasi keuangan yang digaungkan berbagai lembaga, kalah nyaring oleh riuhnya promo besar.
Bagi para pegila belanja, Harbolnas memberi sensasi seolah hidup sedang dibereskan, padahal kita hanya merapikan kecemasan dengan barang baru. Keranjang belanja bukan hanya kumpulan barang, melainkan daftar harapan: wajan baru agar dapur terasa lebih hidup, sepatu baru agar percaya diri naik setingkat, parfum murah meriah agar kita tidak terlihat letih di kantor. Belanja menjadi cara untuk merapikan mood yang acak-acakan.
Tetapi di balik layar pesta diskon itu, ada strategi dagang yang lihai. Harga dinaikkan lalu diturunkan sedikit, bundling yang terlihat murah, padahal membuat kita membeli lebih banyak, ongkir yang “gratis”, tetapi berpindah ke harga barang.
Tidak selalu culas, tetapi jelas bukan amal jariyah. Platform dan brand ingin trafik; konsumen ingin rasa “menang”. Maka terciptalah simbiosis yang aneh: semua orang senang, meski tak semuanya benar-benar untung.
Harbolnas menjadi semacam cermin mental kita sebagai bangsa konsumen: betapa mudahnya kita berlari menuju sesuatu yang terlihat murah, betapa gampangnya merasa kurang. Ia memperlihatkan perbedaan mendasar antara mental “miskin” dan “kaya” — bukan soal saldo, tetapi soal rasa cukup. Pihak yang satu didorong rasa takut kehilangan, yang lain digerakkan keyakinan bahwa apa yang dimiliki sudah lebih dari cukup untuk hidup hari itu.
Ritual ini lucu, sekaligus getir: pesta belanja yang membuat kita seolah lebih punya, padahal sering kali sekadar membuat dompet kita lebih tipis dan hati kembali gelisah, beberapa hari kemudian.

Dahaga belanja
Harbolnas tidak lagi soal transaksi, tapi tentang cara kita mengobati kekosongan yang tak pernah kita akui. Kita ingin merasa punya kendali atas hidup yang semakin riuh, dan membeli barang sering menjadi tombol cepat untuk menghadirkan ilusi itu. Klik, centang, bayar, tuntas. Seolah sebait hidup dibereskan dalam tiga langkah. Padahal, rasa sesak yang kita simpan tetap tinggal di sudutnya sendiri, hanya tertutup aroma plastik baru.
Di balik antusiasme itu tersimpan sebuah pola lama: kita sering menyamakan kepemilikan dengan kesejahteraan. Barang yang bertambah dianggap tanda hidup yang maju. Padahal banyak di antara kita yang tak sedang meloncat naik, hanya berputar dalam lingkar kecil keinginan.
Harbolnas memperlihatkan paradoks itu dengan jelas. Kita merasa sedang mendapat kuasa, padahal yang berkuasa justru dorongan untuk tampil cukup, tampil mampu, tampil terhubung dengan dunia yang serba cepat.
Ada pula semacam tekanan sosial yang jarang kita sadari. Ketika lini masa dipenuhi unboxing, rekomendasi barang, dan testimoni “harga tinggal separo”, ada sentakan halus dalam diri: jangan sampai tertinggal.
Dalam Prospect Theory, Daniel Kahneman & Amos Tversky dijelaskan bahwa manusia lebih sensitif terhadap potensi keuntungan kecil yang terasa pasti, dibanding manfaat besar yang sifatnya abstrak. Harbolnas memanfaatkan pola ini: diskon 10 persen terasa lebih nyata daripada manfaat menabung 100 ribu.”
Baca juga: Creators Lab mengajari perempuan buat dan manfaatkan konten video
Industri bekerja di wilayah “emosi”: bukan logika pembelian, tapi fear of missing out. Orang dibuat khawatir, jangan sampai jadi satu-satunya yang tidak ikut menikmati “pesta tahunan”. Padahal, pesta itu sering lebih mirip dengan antrean panjang menuju rasa puas yang tak pernah stabil. Kita merayakan bersama, lalu menyesal sendirian.
Di sisi lain, gaya hidup impulsif ini turut dibantu oleh algoritma yang bekerja seperti penjaga toko yang terlalu ramah. Ia mengingatkan apa yang pernah kita lihat, menawari hal yang tak kita cari, dan menyodorkan barang yang sebenarnya tidak kita pikirkan. Setiap penawaran terasa personal, seperti bisikan privat yang berkata “ini untukmu”. Kita merasa disapa, padahal kita hanya sedang dibaca.
Pusat dari semuanya kembali pada satu hal: kebutuhan kita akan rasa aman. Kita ingin merasa “cukup” tanpa harus membangun kecukupan itu dari dalam diri.
Harbolnas memberi jalan pintas, walau kita tahu jalan itu berakhir di tempat yang sama: layar kosong, dompet lebih tipis, dan keinginan yang datang lagi besok pagi.
Rasa cukup
Pada akhirnya, Harbolnas mengajak kita bertanya ulang: apa sebenarnya yang kita kejar? Harga murah, sensasi menang, rasa punya, atau sekadar jeda dari rutinitas yang sering terasa monoton? Kadang kita tak benar-benar menginginkan barangnya.
Kita hanya ingin merayakan kesempatan untuk merasa beruntung, meski keberuntungan itu sering dibangun dari potongan harga yang sudah dihitung matang oleh algoritma.
Kita hidup pada zaman ketika identitas bisa terasa rapuh, seperti kertas nota yang mudah kusut. Banyak orang membangun citra “cukup” dari apa yang tampak: punya ini, bisa beli itu, ikut promo ini, dapat akses itu.
Maka Harbolnas berubah menjadi panggung kecil tempat kita memberi tahu dunia bahwa kita mampu bersenang-senang. Walaupun, di balik itu, ada sebagian kita yang hanya ingin meredakan kecemasan kecil: bahwa hidup orang lain tampak lebih nyaman, lebih fun, lebih punya pilihan. Sementara hidup kita sedang kehabisan warna.
Jika ditarik lebih jauh, budaya belanja impulsif yang disulut oleh Harbolnas memperlihatkan cara masyarakat modern mencari pelarian.
Dahulu, orang menenangkan diri dengan tidur siang, ngobrol dengan tetangga, atau duduk memandangi halaman.
Baca juga: Begini cara hindari chat penipuan saat belanja online menjelang Lebaran
Sekarang, pelarian kita datang dalam bentuk notifikasi “Flash Sale segera berakhir”. Ada kesan mendesak, seolah kebahagiaan sedang membuka jendela dan kita harus cepat melompat masuk. Padahal jendela itu muncul setiap pekan, bahkan setiap hari, hanya berganti nama dan tagline.
Namun di balik semua kehebohan itu, ada peluang yang mungkin bisa kita genggam: kesempatan untuk mengenali diri. Untuk memahami kapan kita benar-benar butuh sesuatu, dan kapan kita hanya sedang butuh diakui.
Membedakan kebutuhan dari keinginan adalah seni kecil yang selalu terasa menantang, tetapi justru di situlah letak kemandirian batin.
Mungkin Harbolnas tidak perlu kita musuhi. Ia hanya perlu kita perlakukan seperti kembang api: dinikmati secukupnya, tanpa harus menyalakan semuanya, sekaligus.
Pada titik tertentu, kita perlu merayakan kemampuan untuk memilih jeda. Untuk berkata: hari ini aku sudah cukup. Dan rasa cukup itu, betapapun sederhana, jauh lebih tahan lama dibanding keranjang belanja yang penuh sesak, tapi kosong setelahnya.
Pewarta : Sizuka
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026