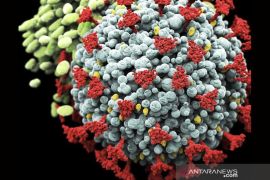Mataram (ANTARA) - Menghadapi COVID-19 tentunya bukan perkara mudah, karena bentuknya yang tak nampak dan bersifat pandemik. Tidak hanya perubahan sosio-ekonomi masyarakat, ritual keagamaan pun dituntut berubah polanya akibat adanya wabah tersebut.
Tulisan ini ingin menegaskan bahwa COVID-19 menuntut adanya tanggungjawab bersama untuk mengatasinya. Tentu dengan latar belakang saya sebagai guru besar Filsafat Islam, maka nuansa tulisan ini bersifat filosofis-Islami.
Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana eksistensi pandemik dari “moderate perspective”. Hal ini penting sebab “menyadari bahwa pandemik ini adalah tanggungjawab bersama” perlu dimulai dari perspektif yang benar akan eksistensinya.
Pandemic: Moderate perspective
Istilah “moderate perspective” saya pakai untuk menengahi dua persepktif ekstrim -- tentunya dalam lingkup ijtihad saya -- tentang eksistensi pandemik COVID-19 yang menimpa dunia saat ini.
Pertama, saintisisme. Istilah ini saya pakai untuk kelompok yang memandang sains sebagai satu-satunya penjelas yang tepat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Kedua, relijiusisme, yaitu kelompok yang membuat putusan-putusan agama terkait COVID-19 tanpa melihat an sich penjelasan sains, bahkan sains dilihat dengan penuh kecurigaan.
Keduanya merupakan bentuk kepongahan yang sama sekali tak menyentuh eksistensi pandemik tersebut, dalam artian mencegah penyebarannya. Jika kedua perspektif tersebut bisa dikatakan sebagai “kesesatan berfikir”, maka penyebabnya bisa bermuara dari dua hal: syubhat atau syahwat, dan atau kedua-keduanya.
Syubhat dalam artian adanya kesamaran pengetahuan seseorang akan suatu fenomena sehingga menghasilkan putusan-putusan konseptual yang keliru. Di sini latar belakang pendidikan memiliki peran vital untuk itu.
Syahwat meliputi kepentingan-kepentingan yang bisa jadi diperlukan untuk memperkuat status-quo diri dalam kelompoknya. Artinya ada ego sentris dalam menerjemahkan musibah. Tentunya dari nalar keagamaan yang sehat. Keduanya tidak dapat diterima.
Untuk itu “moderate perspective” atau dalam artian wasathiyah perlu dilakukan untuk menghasilkan putusan-putusan konseptual yang adil. Adil yang dimaksud di sini adalah tidak ektrim kanan apalagi ekstrim kiri. Definisi umum tentang adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.
Oleh karena itu, penjelasan-penjelasan sains tekait COVID-19 haruslah dikonfirmasi kepada Agama, atau agamawan perlu duduk bersama dengan saintis “mengobrol” dengan mengesampingkan segala bentuk kepentingan yang ada, dalam artian diskusi yang murni akademis (purely academic), sehingga tampak bahwa agama dan sains sejatinya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.
Dalam filsafat Islam, “moderate perspective” dapat ditopang dengan pemahaman ontologis dan epistemologis. Pemahaman ontologis terkait dengan hakikat sesuatu bahwa apa yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya adalah berasal dari Tuhan, termasuk musibah pandemik.
Laporan Alquran Qs. Al-Hadid: 22 menunjukkan hal itu secara eksplisit, yakni bahwa segala bentuk kejadian telah ada dalam cetak biru, blueprint Ilmu Allah atau disebut Lauh Mahfudz.
Ini merupakan nalar kehidupan beragama agar menilai sebab-akibat sebagai sesuatu yang possible, bukan sesuatu yang mutlak. Artinya, ada kehendak Allah di setiap peristiwa.
Maksud secara epistemologis adalah berdasarkan nalar kebiasaan atau bahasa agama disebut ‘adat.
Jika difahami bahwa pandemik COVID-19 sebagai musibah non-alam, artinya dalam nalar kebiasaan ada campur tangan manusia (bima kasabat aydinnas). Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk melakukan kerja-kerja ilmiah untuk dapat memprediksi ataupun mengantisipasi setiap kejadian.
Kedua pemahaman tersebut tidaklah dapat dipisahkan. Pemahaman pertama menunjukkan eksistensi manusia sebagai hamba Allah, dalam artian apa yang terjadi dalam dirinya dan sekitarnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Sementara pemahaman kedua merujuk pada eksistensi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Condong pada salah satunya dalam membaca eksistensi pandemik merupakan pemahaman yang keliru, sebagaimana dalam saintisisme ataupun relijiusisme.
COVID-19 sebagai tanggungjawab bersama
Dalam literatur Islam, virus semacam COVID-19 dapat diistilahkan sebagai waba’ dan tha’un. Keduanya dikategorikan sebagai penyakit menular, atau dalam istilah medis disebut epidemik dan pandemik. Bedanya, tha’un lebih berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dengan cepat.
Ibn Sina (1037 M), filosof sekaligus pakar medis muslim abad pertengahan menjelaskan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh mikroorganisme (kainat daqiqah) yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan bisa menular melalui udara atau sentuhan fisik.
Oleh karena itu, menjaga kebersihan badan dan menjaga jarak fisik dan sosial adalah solusi yang ditawarkan Ibn Sina untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Selain itu, kondisi kejiwaan, khususnya bagi yang “terpapar virus” agar tetap tenang, dalam artian tidak panik, karena dalam ketenangan jiwa itu ada pengobatan.
Al-wahm nisf al-da-i wa al-ithmi’nan nishfu al-dawa-I wa al-shabr bidayah al-Syifa’. Sikap tenang bagi yang “belum terpapar” sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan kerja-kerja bersama yang produktif, terukur, dan sistematis.
Sejatinya, apa yang dilakukan oleh Ibn Sina sebagaimana dimaksud tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Nabi, dengan mengeluarkan sabda yang juga berfungsi sebagai kebijakan publik, dilihat posisi Nabi sebagai kepala pemerintahan waktu itu. Sabda Nabi:
“…Jika di suatu wilayah ada wabah, maka jangan memasukinya. Jika terjadi di tempat sendiri, jangan tinggalkan tempat itu …bagi mereka yang terpapar agar dijauhkan dari yang sehat.”
Jika diperhatikan, kebijakan-kebijakan seperti menjaga kebersihan, karantina wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi diri, anjuran untuk tidak panik dan lain sebagainya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan orang-orang terdahulu.
Ini artinya, kebijakan-kebijakan itu sudah dilakukan melalui prosedur ilmiah.
Kebijakan tersebut juga telah diterjemahkan dalam bentuk putusan-putusan agama atau dalam istilah Islam disebut fatwa.
Perlu dicatat, filosofi fatwa dalam Islam adalah pendapat yang dikeluarkan oleh ulama secara institusional. Dalam konteks bernegara adalah lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.
Maka, pendapat individu dari seorang yang dianggap tahu masalah agama tidaklah dihukumi sebagai fatwa.
Dalam perspektif filsafat Islam, negara ibarat tubuh manusia. Sebagai satu kesatuan organis, seluruh tubuh harus menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Ini artinya, jika ada masalah pada salah satu organ akan mengakibatkan sakit seluruh badan, atau dalam hal bernegara akan mengganggu stabilitas publik (negara).
Ide bernegara muncul karena watak manusia yang cenderung bermasyarakat sesuai dengan sifatnya sebagai makhluk sosial (madaniy bi al-thab’i).
Kecenderungan itu tentunya menuntut adanya aturan-aturan dan norma-norma yang harus ditaati. Dalam situasi itu masyarakat mengangkat dari antara mereka pemimpin untuk menjaga aturan-aturan itu tetap terlaksana yang kemudian membentuk suatu pemerintahan.
Sebagai satu kesatuan tubuh, pemerintah dapat diibaratkan kepala karena dianggap mewakili jiwa rasional, sementara agamawan adalah hati karena dianggap mewakili jiwa spiritual dan masyarakat adalah badan karena dianggap mewakili jiwa emosional.
Secara fungsional, semuanya memiliki keterhubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, karena ketidakadaan salah satunya mengakibatkan sebuah komunitas tidak layak disebut negara.
Dalam konsep jiwa, rasionalitas dan spiritualitas akan menjadi tidak stabil jika ada keguncangan emosional. Jika dikaitkan dengan tata bernegara, sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika terjadi kegaduhan publik.
Dalam konteks kebijakan COVID-19 di Indonesia dibutuhkan sekali kesadaran bernegara sebagai satu kesatuan tubuh, bahwa pandemik itu adalah masalah bersama. Ini artinya upaya mengatasi pandemik itu bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama.
Selain kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggapi penyebaran COVID-19, dukungan masyarakat dan penerjemahan kebijakan dalam kerja-kerja kolegial yang kreatif sangatlah diperlukan. Wa billahi nasta’in…
*Penulis, Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M.Ag adalah Guru Besar Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.