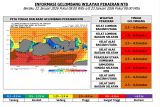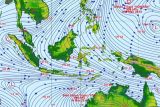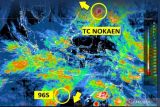Palu (ANTARA) - Beberapa hari terakhir jagad media massa dan sosial dihebohkan dengan penemuan pagar bambu di perairan Tangerang, Provinsi Banten, sepanjang 30,16 kilometer. Khalayak pun bertanya-tanya siapa gerangan pemilik dan untuk keperluan apa pagar tersebut dibuat. Sejumlah spekulasi bermunculan.
Beberapa nama korporasi disebut-sebut sebagai pemilik pagar tersebut. Sejumlah pejabat dari instansi terkait saling menuding. Di tengah kebisingan publik menerka siapa dan untuk apa pagar itu dibuat, TNI AL memutuskan untuk membongkar paksa. Maka serta merta pagar bambu tersebut dicabut satu-persatu.
Kendati aktor dan prayojana pembuatan pagar tersebut masih remang-remang, namun rasanya tidak sulit menangkap isyarat atau muatan yang dikandung dalam simbol pagar bambu tersebut. Sebab, secara umum, masyarakat Indonesia selama ini cukup kenyang mengunyah kearifan-kearifan tentang pagar sehingga ketanyaman rasa semiosis untuk tema yang satu ini cukup terjaga dengan baik. Di antara kearifan “pagar” yang lazim kita dengar, semisal, “ibarat pagar makan tanaman,” “lompat pagar,” “jangan pernah merobohkan pagar kalau tidak tahu untuk apa didirikan,” serta ungkapan-ungkapan yang lain.
Kata “pagar” dalam ungkapan-ungkapan tersebut, seturut penghayatan rasa kebahasaan masyarakat, sama sekali tidak bermakna denotatif (apa adanya), melainkan sudah bermakna konotatif (kiasan). Kebiasaan memainkan bahasa kiasan itulah yang memandu dan mengerangkai makna ketika melihat fenomena pagar bambu yang viral tersebut.
Salah satu makna simbolik dari pagar yang paling sulit dibantah tentu saja adalah simbol kepemilikan. Seseorang memagari tanah karena merasa sebagai pemilik tanah tersebut. Demikian juga laut dipagari karena merasa empu di kawasan tersebut. Yang jadi soal kemudian, bagaimana proses peralihan laut dari semula tidak ada pemilik menjadi berpemilik? Alur bidak catur yang mana yang dipermainkan? Bagaimana pula kalau, semisal saya atau sampeyan, punya hasrat yang sama untuk mengapling laut tersebut, apakah juga dibolehkan? Kalau “ya”, maka tamatlah harmoni kehidupan di muka bumi ini. Akan terjadi gelombang penjarahan kawasan laut yang membabibuta, setelah akses kepemilikan lahan di darat kian sulit dan sempit.
Nalar common sense setiap kita pasti menolak aksi destruktif semacam itu. Mengapa, karena merusak alam secara radikal kompatibel dengan bunuh diri kolektif. Fitrah manusia, sejatinya, adalah alam itu sendiri. Ikhwan al-Shafa dalam kitab Rasail mewedar bagaimana hubungan manusia dan alam itu sangat bersifat eksistensial. Jalinan manusia dan alam ada dalam level hakikat keberadaan. Bukan bersifat intelektual atau emosional yang hanya menggelora di pikiran dan perasaan. Alhasil, dengan relasi semacam itu, sangat sulit untuk saling melukai, apalagi saling menghabisi.
Al-Shafa menyebut manusia sebagai “alam shaghir” (alam kecil atau microcosmic). Sedangkan alam disebut sebagai “insan kabir” (manusia besar atau macroanthropos). Penjelasan singkat dari istilah ini adalah bahwa kalau ingin memahami alam, lihatlah manusia. Karena manusia dengan segala kompleksitas struktur biologis dan psikologisnya merupakan cermin dari wujud alam semesta. Sebaliknya, jika ingin memahami manusia, lihatlah alam. Sebab, alam semesta dengan ragam dan kompleksitas bagiannya merupakan gambaran dari manusia.
Manusia tersusun dari dualitas badan dan ruh. Alam pun demikian. Segala aspek yang dibutuhkan manusia sudah pasti juga dibutuhkan alam semesta. Jika ada perbedaan, maka itu hanya terletak pada akal atau rasio. Manusia mengungguli alam karena kepemilikan atas akal. Pada akal inilah pusat kehidupan manusia dan keharmonisan alam semesta dibentuk dan dikendalikan. Eksplanasi sederhana mengenai akal dapat dilihat dalam kereta kuda. Kendaraan tersebut punya roda untuk bergerak dan kuda sebagai penarik. Namun bagaimana memfungsikan dan mengarahkan kereta kuda ke tujuan yang tepat sangat bergantung pada kusir. Tanpa kusir, kereta tersebut akan bergerak tanpa arah dan manfaat. Kusir di sini adalah simbol dari peran akal, sedangkan kereta kuda adalah kehidupan alam semesta.
Jalinan eksistensial ini ssangat sublim. Selain itu juga saling menjadi kausa atau penyebab bagi kondisi yang lain. Kebaikan dan keselarasan alam semesta merupakan ekstensi (keluasan) dari kebaikan dan keselarasan manusia. Sebaliknya, kerusakan alam serta merta akan berdampak pada kehidupan manusia yang juga tidak baik.
Manusia dengan akalnya perlu pepeling agar mawas. Manusia yang mawas akan bertindak bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan saat ini, di tengah alam yang kiat sulit dimengerti alurnya. Ketidakmengertian alur alam ini dalam pustaka ilmiah sering diungkapkan dengan istilah anomali. Alam mengalami anomali dalam berberapa aspeknya, termasuk dalam hal iklim. Sejumlah bencana alam yang menghiasi etalase media massa dan sosial mutakhir ini, seperti kebakaran hebat di Los Angeles, badai Salju di Houston dan New Orleans, banjir di sejumlah daerah di Indonesia berikut bencana alam yang lain, konon ditengarai akibat anomali alam.
Anomali alam ini harus dihentikan. Segala hal yang potensial mengawetkan anomali alam juga harus dicegah. Boleh jadi, pemagaran laut Tangerang yang menghebohkan itu akan berpotensi menjadi penyebab meningkatnya eskalasi anomali atau, kalau tidak, menyebabkan anomali berikutnya. Oleh karena itu sudah tepat dibongkar. Cukuplah kesadaran anak-anak bangsa dicekoki pengalaman “pagar makan tanaman.” Jangan lagi ditambah “pagar makan lautan”.
*) Penulis adalah dosen Filsafat UIN Datokarama Palu